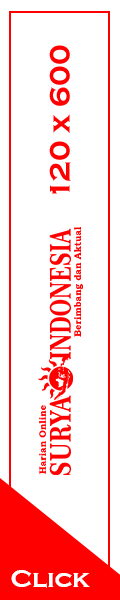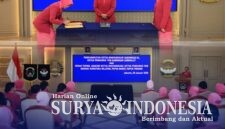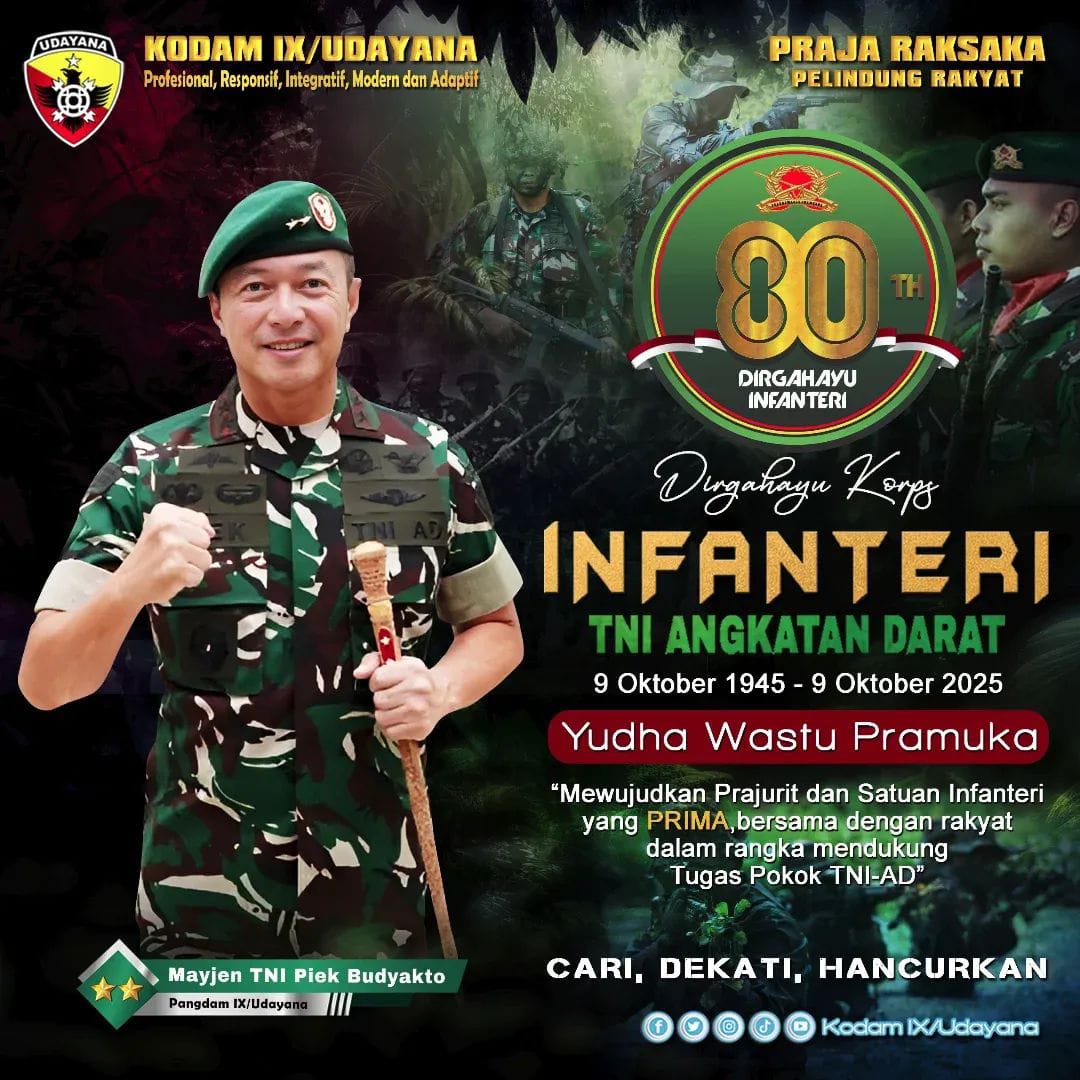Filsafat:
Filsafat Sejarah dan Sastra
Oleh Djoko Sukmono
Sastra adalah kefasihan yang bermanifestasi dalam bentuk tulisan maupun Narasi. Dia juga Bisa berbentuk Sastra Filsafat, Roman, Nobel, Puisi, Prosa, dan Esai.
Sastra sejarah, bahkan bisa berbentuk Sastra Mantra yang banyak ditemukan pada ayat-ayat kitab suci.
Sastra tidak membutuhkan pembenaran.
Dia adalah otonom dengan penyajian bentuk-bentuk Keberadaan ontologis yang indah.
Dia hanya Bisa disimak baik-baik dan dihayati.
Filsafat adalah pertentangan pikiran seluas-luasnya, sedalam dalamnya dan secara radikal dengan penggunaan methodologi yang bernama Reflektif Thinking.
Epos
Epos adalah bidang sastra. Ia merupakan kisah tentang kehidupan sosial manusia yang dikemas dengan apik, sarat dengan analogi, dan lebih dekat pada mitologi ketimbang pada eskatologi.
Epos tidak menuntut bukti; ia menuntut keyakinan dalam bentuk imajinasi kolektif. Ia hidup di dalam cerita, dalam simbol, dalam ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ia tidak tunduk pada waktu linear, melainkan berputar di dalam lingkaran makna yang terus diperbarui.
Eskatologi, sebaliknya, digunakan untuk memahami kitab suci. Ia berbicara tentang akhir, tentang tujuan, tentang penyelesaian yang mutlak. Sedangkan epos adalah dunia yang tak pernah selesai — ia hidup karena keterbukaannya.
Terlepas dari apakah itu Mahabharata, Ramayana, Odyssey, atau kisah-kisah Nusantara, epos tetaplah epos: narasi besar tentang manusia, dewa, dan dunia yang dijalin tanpa harus menagih bukti faktual.
Dalam hal sistematika, epos sangat dipengaruhi oleh cara berpikir lama yang bersifat statifikatif — cara berpikir yang menempatkan segalanya pada tatanan kosmis: yang suci di atas, yang profan di bawah.
Ia tidak bisa dibuktikan keberadaannya, karena ia berdiri di wilayah makna, bukan fakta. Ia hanya diterima begitu saja, tanpa alasan — sebab ia hidup bukan dari logika, melainkan dari kesepakatan batin kolektif.
Biarlah epos tetap ada, sebab itu bagian dari budaya. Ia adalah arsip batin manusia sebelum rasionalitas lahir, sebelum sejarah menjadi disiplin ilmu.
Namun yang jelas: epos bukanlah sejarah.
Sebab sejarah adalah peristiwa konkret dan faktual, bukan alegori atau mitos.
Sejarah harus memenuhi sifat yang disebut trans-historis — yaitu memiliki lintasan peristiwa yang terhubung, saling berkesinambungan, dan dapat diuji secara empiris.
Karena itu, metodologi yang digunakan untuk memahami dan mengungkap sejarah adalah metodologi yang disebut rasio historis.
Rasio
Rasio historis menuntut bukti, kontinuitas, dan kesadaran akan sebab dan akibat. Ia tidak berpihak pada kepentingan siapa pun, tidak mengabdi pada ideologi, melainkan pada pengetahuan yang ilmiah.
Segala yang di luar itu, hanyalah narasi — bukan sejarah.
Maka dalam filsafat sejarah, rasio historis adalah poros metodologinya. Ia menjadi dasar untuk membedakan antara kepercayaan dan pengetahuan, antara kisah dan peristiwa.
Sejarah
Sejarah bukan kepercayaan.
Sejarah bukan agama.
Sejarah adalah proses, tahapan, dan menjadi.
Ia merupakan peristiwa sosial yang otentik — bukan hasil imajinasi kolektif, melainkan hasil dialektika nyata antara manusia dan dunianya.
Tidak ada sejarah tentang individu manusia, sekalipun ia diklaim sebagai individu terpilih, bahkan sebagai yang dipilih oleh Yang Adikodrati.
Yang ada adalah sejarah tentang relasi — antara individu dan masyarakat, antara gagasan dan materi, antara kesadaran dan kondisi.
Namun, anak-anak manusia cenderung lebih menyukai kisah ketimbang sejarah. Kisah memberi kenyamanan, sebab ia bisa dijadikan dongeng; ia menenteramkan hati, sementara sejarah justru mengguncang kesadaran.
Ingatlah, materialisme historis-dialektis adalah sejarah manusia dan materi. Keduanya berdialektika dalam rangka perkembangan dan perubahan.
Tidak ada manusia tanpa materi, dan tidak ada materi yang bermakna tanpa aktivitas manusia.
Namun, sejarah tetap harus berpijak pada yang empiris dan pada landasan logis. Sebab tanpa keduanya, sejarah jatuh menjadi dogma, dan dogma adalah bentuk baru dari ketidaktahuan.
Kini, dalam sistem kapitalistik dewasa ini, justru materi menindas manusia. Manusia direduksi menjadi barang ekonomi, menjadi komoditas, menjadi angka di layar pasar.
Struktur sosial-ekonomi kapitalistik adalah mesin raksasa yang menindas manusia — namun dengan cara yang lembut, tanpa cambuk, tanpa darah.
Anehnya, mereka yang ditindas sering tak menyadari penindasan itu. Ia telah menjadi kebiasaan, rutinitas, bahkan kebanggaan.
Orang bekerja bukan untuk hidup, tetapi untuk mempertahankan mekanisme yang menindas hidup itu sendiri.
Sistem kapitalistik telah menjadi konkret di dalam sejarah; ia telah menjelma menjadi budaya.
Ia tidak lagi sekadar sistem ekonomi, melainkan struktur kesadaran. Dan di situlah kemenangan kapitalisme: ketika sejarah — bahkan kesadaran historis manusia — berada di dalam genggamannya.
Lalu bagaimana jika semuanya telah menjadi seperti ini?
Apakah masih bisa dilawan?
Sukarno telah dikalahkan olehnya.
Uni Soviet pun demikian.
Yugoslavia juga.
Dan masih banyak negara lainnya — satu per satu tumbang, bukan oleh senjata, melainkan oleh daya pesona sistem yang menjanjikan kemakmuran namun menanam keterasingan.
Maka muncul pertanyaan yang mengguncang zaman:
Bagaimana dengan Republik Rakyat Tiongkok?
Apakah Tiongkok adalah contoh kebangkitan komunisme?
Ataukah ia adalah bentuk kapitalisme yang mengenakan jubah merah revolusi?
Pertanyaan ini bukan sekadar geopolitik, melainkan pertanyaan filsafat sejarah:
Apakah ideologi dapat bertahan ketika ia berhadapan dengan struktur ekonomi global yang menaklukkan semua nilai menjadi nilai-tukar?
Kini, batas antara sosialisme dan kapitalisme menjadi kabur. Keduanya berbaur di dalam satu mekanisme: industrialisasi, pasar, dan kontrol teknologi.
Mungkin di sinilah ironi sejarah: bahwa setiap revolusi yang menang akhirnya menjadi sistem baru yang memenjarakan semangat revolusinya sendiri.
Dan pada akhirnya, manusia kembali menjadi objek — bukan subjek — dari sejarah.
Ia dibentuk, diarahkan, dimanipulasi oleh sistem yang ia ciptakan sendiri.
Sejarah menjadi milik mereka yang menguasai produksi makna, bukan mereka yang hidup di dalamnya.
Namun selama kesadaran masih ada,
selama manusia masih sanggup menulis, mengingat, dan bertanya,
sejarah belum selesai.
Mungkin dari reruntuhan kapitalisme global ini, akan lahir epos baru — bukan tentang para dewa, melainkan tentang manusia yang berusaha menjadi manusia kembali. ***)